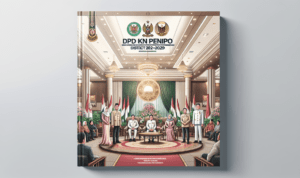hariangarutnews.com – Ketika Kementerian Dalam Negeri resmi menunjuk Garut sebagai tuan rumah Nasionalisme Goes to School 2026, pesan yang terpancar jauh melampaui seremoni seremonial. Kabupaten yang identik dengan dodol dan panorama pegunungan ini tiba-tiba naik kelas menjadi laboratorium kebangsaan. Bukan sekadar event, Nasionalisme Goes to School berpotensi mengubah cara generasi muda memaknai merah putih. Pilihan lokasi ini terasa menarik, sebab Garut merepresentasikan Indonesia luar metropolitan, tempat identitas lokal bersentuhan langsung dengan narasi keindonesiaan.
Nasionalisme Goes to School selama ini sering dianggap sebagai program sosialisasi nilai dasar negara pada pelajar. Namun, penunjukan Garut membuka peluang reinterpretasi yang lebih segar. Pendidikan kebangsaan tidak cukup berhenti di hafalan Pancasila atau upacara Minggu pagi. Ia perlu menyentuh keseharian siswa, budaya daerah, juga tantangan digital. Lewat panggung 2026 nanti, Garut bisa menjadi contoh bagaimana nasionalisme diramu ulang agar tetap relevan, tanpa kehilangan akar sejarah maupun nilai lokal.
Makna Strategis Nasionalisme Goes to School di Garut
Memilih Garut sebagai pusat Nasionalisme Goes to School 2026 menyiratkan arah kebijakan yang patut dicermati. Selama bertahun-tahun, wacana kebangsaan sering terpusat di kota besar. Kini, perhatian beralih ke daerah yang kerap dipandang sebagai “pinggiran”. Garut menyimpan sejarah panjang pergerakan rakyat, tradisi pesantren kuat, serta keberagaman komunitas. Kombinasi faktor ini menjadikan wilayah tersebut panggung ideal untuk menguji model pendidikan nasionalisme yang lebih inklusif.
Dari sudut pandang personal, saya melihat langkah ini sebagai koreksi halus atas pendekatan nasionalisme seragam. Nasionalisme Goes to School seharusnya tidak mendorong keseragaman rasa, melainkan kesatuan tujuan. Setiap daerah memerlukan cara berbeda dalam menanamkan cinta tanah air. Garut memiliki budaya Sunda, tradisi agraris, sampai geliat ekonomi kreatif. Seluruh unsur itu bisa dirangkai menjadi bahan ajar hidup tentang bagaimana warga menjaga tanah, air, bahasa, juga solidaritas sosial.
Kebijakan Kemendagri tersebut juga mengirim sinyal bahwa nasionalisme abad ke-21 perlu menyentuh isu nyata: ketimpangan wilayah, krisis lingkungan, transformasi digital. Garut dikenal rentan bencana, bergantung pada sektor pertanian, sekaligus mulai terdorong wisata alam. Dalam konteks Nasionalisme Goes to School, pelajar dapat diajak membaca nasionalisme melalui kerja menjaga sawah, sungai, hutan, serta ruang publik digital. Artinya, cinta tanah air diterjemahkan ke aksi konkret, bukan hanya slogan di dinding kelas.
Transformasi Cara Pandang Generasi Muda
Program Nasionalisme Goes to School di Garut berpeluang menggeser cara pandang pelajar tentang identitas kebangsaan. Selama ini, nasionalisme kerap tampil kaku, berkutat pada seragam, baris-berbaris, atau hafalan teks. Pendekatan itu penting, namun tidak lagi cukup menghadapi generasi yang tumbuh bersama gawai. Di Garut, program bisa dirancang agar siswa belajar nasionalisme melalui proyek nyata, misalnya dokumentasi sejarah lokal, pemetaan situs budaya, atau kampanye lingkungan berbasis media sosial.
Saya memandang pendekatan proyek seperti itu jauh lebih efektif daripada ceramah satu arah. Nasionalisme Goes to School dapat memfasilitasi kolaborasi lintas sekolah, desa, juga komunitas. Siswa diajak keluar kelas, menyusuri kampung, mewawancarai tetua adat mengenai kisah perjuangan masa silam. Mereka kemudian mengolah cerita itu jadi film pendek, komik digital, atau podcast. Identitas kebangsaan tidak lagi abstrak, melainkan hadir sebagai kisah keluarga, tradisi pasar, ritual panen, juga musik tradisional yang masih hidup.
Perubahan cara pandang ini penting agar nasionalisme tidak sekadar reaksi emosional saat tim nasional bertanding. Di Garut, pelajar dapat disadarkan bahwa nasionalisme berarti solidaritas saat bencana, kejujuran ketika mengelola dana desa, bahkan kepedulian pada produk lokal. Nasionalisme Goes to School bisa menjadi jembatan antara idealisme di buku pelajaran dengan kenyataan pahit seperti kemiskinan, pengangguran muda, juga kerentanan petani. Dari sana, nasionalisme muncul sebagai kesadaran bertanggung jawab memperbaiki keadaan.
Garut Sebagai Laboratorium Kebangsaan Masa Depan
Menjadikan Garut sebagai tuan rumah Nasionalisme Goes to School juga membuka peluang eksperimen pendidikan publik berbasis komunitas. Pemerintah daerah dapat mengintegrasikan program ini dengan agenda desa, pesantren, serta lembaga seni. Misalnya, membuat pekan budaya kebangsaan yang melibatkan padepokan silat, sanggar jaipongan, komunitas fotografer muda, juga UMKM lokal. Kegiatan seperti itu menyatukan warga lintas usia, sehingga pembelajaran nasionalisme tidak terbatas pada pelajar sekolah formal saja.
Selain itu, Garut memiliki modal geografis kuat untuk menjabarkan konsep cinta tanah air secara konkret. Gunung, hutan, kolam air panas, hingga pantai selatan menyimpan isu konservasi yang nyata. Nasionalisme Goes to School bisa mengajak siswa mengadopsi titik-titik alam tertentu sebagai “ruang asuh”. Mereka terlibat kegiatan penanaman pohon, bersih sungai, pemantauan sampah wisata, juga kampanye wisata ramah lingkungan. Dengan begitu, sikap menjaga bumi pertiwi hadir lewat pengalaman fisik, bukan sekadar teori di buku IPS.
Dari sudut pandang saya, elemen paling penting ialah keberanian menjadikan pelajar sebagai subjek, bukan objek. Nasionalisme Goes to School di Garut tidak boleh berhenti di tingkat seremoni pembukaan meriah. Ruang partisipasi perlu terbuka lebar: forum diskusi, lokakarya kreatif, hackathon ide sosial, hingga kompetisi konten digital bertema kebangsaan. Melalui cara tersebut, generasi muda Garut tidak hanya menerima materi, tetapi juga memproduksi narasi kebangsaan yang relevan dengan pengalaman mereka sendiri.
Tantangan Implementasi Nasionalisme Goes to School
Meskipun prospek tampak cerah, implementasi Nasionalisme Goes to School di Garut menghadapi beberapa tantangan mendasar. Pertama, kesiapan guru. Banyak pendidik masih terbiasa dengan metode ceramah. Perubahan ke model partisipatif membutuhkan pelatihan serius, juga dukungan kurikulum. Tanpa peningkatan kapasitas, program berisiko menjadi slogan kosong. Guru perlu merasa aman bereksperimen, tidak takut dinilai menyimpang saat mengajak siswa keluar zona nyaman.
Kedua, infrastruktur. Garut memiliki daerah terpencil dengan akses internet terbatas. Padahal, dimensi digital penting untuk kampanye nasionalisme yang menyasar generasi muda. Pemerintah pusat, daerah, juga swasta perlu bergandengan menutup kesenjangan ini. Nasionalisme Goes to School justru dapat dimanfaatkan sebagai alasan kuat mempercepat pemerataan akses. Jika tidak, hanya sekolah tertentu yang menikmati program penuh, sedangkan pelajar di pelosok tertinggal lagi.
Dari sisi saya, tantangan paling halus justru menyangkut cara menyampaikan pesan. Nasionalisme sering dipakai untuk membungkam kritik. Ini bahaya laten. Program di Garut sebaiknya justru mengajarkan bahwa cinta tanah air selalu memberi ruang bagi pertanyaan kritis. Siswa perlu diajak berdialog mengenai korupsi, ketimpangan, bahkan konflik sosial. Mereka harus paham bahwa mengoreksi pemerintah atau kebijakan bukan berarti kurang nasionalis. Sebaliknya, sikap itu bagian dari tanggung jawab warga negara.
Integrasi Nilai Lokal dengan Narasi Nasional
Salah satu peluang terbesar Nasionalisme Goes to School di Garut ialah integrasi nilai lokal ke narasi nasional. Budaya Sunda sarat ajaran lemah lembut, tata krama, juga gotong royong. Nilai tersebut sejalan dengan Pancasila. Guru, tokoh masyarakat, serta pelajar dapat bersama-sama merumuskan materi pembelajaran yang menggabungkan kisah lokal dengan teks konstitusional. Misalnya, menafsirkan sila keempat lewat tradisi musyawarah kampung, bukan hanya melalui definisi buku pelajaran.
Namun integrasi ini membutuhkan sensitivitas. Identitas lokal perlu dirawat tanpa menjelma sekat. Nasinalisme Goes to School harus menunjukkan bahwa kebanggaan terhadap bahasa dan adat Sunda tidak bertentangan dengan rasa memiliki atas Indonesia. Justru sebaliknya, keragaman itulah yang membentuk kekuatan kolektif. Dalam pandangan saya, jika Garut sukses menarasikan harmoni semacam ini, daerah lain dapat menirunya dengan menonjolkan budaya setempat, entah itu Minangkabau, Bugis, Dayak, atau Betawi.
Integrasi nilai lokal juga membuka kesempatan bagi pelajar untuk bertemu lintas daerah secara virtual. Program Nasionalisme Goes to School dapat memfasilitasi kelas kolaboratif antara siswa Garut dan siswa dari provinsi lain. Mereka saling memperkenalkan bahasa, makanan, hingga lagu daerah. Pertukaran sederhana itu sanggup mengikis stereotip, menumbuhkan rasa ingin tahu sehat, serta memperkaya pandangan bahwa Indonesia bukan hanya apa yang tampak di kota sendiri.
Peran Generasi Digital sebagai Penggerak
Generasi muda Garut hari ini tumbuh bersama gawai, media sosial, serta budaya viral. Kekuatan tersebut sering dipandang ancaman bagi fokus belajar, padahal justru bisa menjadi aset bagi Nasionalisme Goes to School. Pelajar mampu memproduksi video pendek, desain grafis, juga tulisan singkat dengan kecepatan tinggi. Jika diarahkan cerdas, kemampuan itu dapat menghidupkan narasi kebangsaan yang lebih segar, kreatif, serta mudah dibagikan lintas platform.
Saya membayangkan lomba konten digital bertema “Nasionalisme dari Kampungku” yang melibatkan sekolah di seluruh Garut. Siswa merekam kehidupan sehari-hari: petani yang bangun sebelum fajar, pedagang kecil ulet, relawan bencana yang sigap, atau guru honorer berdedikasi. Kisah-kisah ini menjadi potret wajah Indonesia dari bawah, jauh dari gemerlap gedung tinggi. Nasionalisme Goes to School kemudian berperan sebagai kurator, mentor, sekaligus panggung bagi karya terbaik.
Selain memproduksi konten positif, generasi digital juga perlu dibekali literasi kritis. Ruang maya penuh hoaks, ujaran kebencian, serta narasi ekstrem. Nasionalisme Goes to School di Garut wajib memasukkan modul literasi media. Pelajar diajak memeriksa sumber, memahami algoritma, serta menyadari bagaimana emosi sering dimanipulasi. Dengan begitu, nasionalisme tumbuh bukan sebagai fanatisme buta, melainkan kapasitas memilah informasi, menolak provokasi, sekaligus menyebarkan pesan persatuan.
Menutup dengan Refleksi: Garut dan Arah Baru Nasionalisme
Penunjukan Garut sebagai tuan rumah Nasionalisme Goes to School 2026 pada akhirnya mengundang refleksi lebih luas tentang arah bangsa. Apakah kita berani meninggalkan pola lama yang menjadikan nasionalisme sekadar ritual? Apakah pemerintah bersedia membuka ruang dialog, bukan hanya mengarahkan dari atas? Saya percaya, jika Garut mampu menjadikan program ini sebagai proses belajar dua arah antara negara serta warga, maka kota kecil di Priangan itu akan dikenang sebagai titik balik cara Indonesia membesarkan generasi baru. Generasi yang bangga pada tanah kelahiran, kritis terhadap ketidakadilan, sekaligus siap merawat rumah besar bernama Indonesia dengan cara nyata, cerdas, juga penuh welas asih.