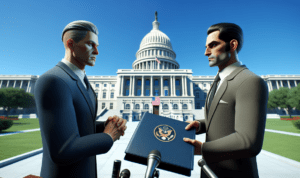hariangarutnews.com – Foto-foto dari Myanmar beberapa bulan terakhir terasa seperti ironi kolektif. Spanduk kampanye berwarna cerah berdiri di depan gedung yang hancur, sementara tentara bersenjata melintas di belakangnya. Di tengah perang saudara yang belum mereda, junta militer justru menyiapkan pemilu, seolah sebuah panggung raksasa tempat foto demokrasi dipamerkan tanpa isi.
Bagi banyak warga, momen ini tidak tampak seperti pesta demokrasi, melainkan sesi foto propaganda. Jalanan sepi, pos pemeriksaan tersebar, dan suara tembakan kerap menggantikan sorak-sorai kampanye. Pertanyaannya: dapatkah pemilu diatur dengan layak ketika negara masih terbelah, banyak lawan politik dipenjara, dan kepercayaan publik terpotong setipis kertas?
Kontras Pedih antara Foto Kampanye dan Realitas
Satu foto bisa menjelaskan apa pun tanpa kata-kata. Di Myanmar, gambar baliho kandidat yang tersenyum berdiri berhadapan dengan rumah yang terbakar akibat konflik bersenjata. Pemandangan semacam itu memperlihatkan jurang lebar antara narasi resmi junta dan kenyataan di lapangan. Rezim berupaya menampilkan foto negara stabil, sementara warga merasakan ketakutan setiap hari.
Penguasa militer memahami betul kekuatan foto. Media pemerintah menampilkan gambar antrean pemilih, rapat koordinasi pemilu, serta pertemuan pejabat pemantau. Semuanya tampak rapi, tertib, dan penuh harapan. Namun, banyak wilayah masih berada di bawah kendali kelompok perlawanan, membuat foto-foto resmi tersebut menjadi potongan realitas yang sangat selektif.
Kita sering diajarkan bahwa pemilu adalah puncak partisipasi rakyat. Tetapi ketika foto TPS dijaga ketat tentara bersenjata, makna partisipasi berubah total. Alih-alih jadi wujud kebebasan, pemungutan suara bergeser menjadi ritual wajib demi legitimasi. Di sinilah ironi terbesar pemilu Myanmar: gambar yang tersaji ke luar negeri bisa tampak demokratis, sementara pengalaman warga di belakang foto penuh tekanan.
Strategi Legitimasi Melalui Lensa Kamera
Dari sudut pandang junta, pemilu ini berfungsi seperti sesi foto studio besar-besaran. Tujuannya bukan sekadar memilih wakil rakyat, melainkan menangkap momen-momen yang kelak dipakai sebagai bukti sahih bahwa mereka mematuhi prosedur demokratis. Foto kotak suara, bilik pemilih, serta pernyataan resmi menjadi aset politik jangka panjang, khususnya menghadapi tekanan internasional.
Saya melihat upaya ini sebagai strategi canggih sekaligus berbahaya. Canggih, karena junta memanfaatkan bahasa visual yang mudah dikonsumsi publik global. Berbahaya, sebab foto-foto tersebut berisiko menutupi suara kritis dari lapangan. Media asing barangkali hanya memperoleh akses terbatas, sehingga gambar yang tersiar kerap berasal dari kanal resmi. Tanpa konteks, foto bisa berubah menjadi alat cuci citra.
Bila kita mengandalkan foto resmi saja, cerita Myanmar akan tampak seperti transisi politik biasa. Ada pemilu, ada kampanye, ada pemilih. Namun, di luar frame, ribuan warga mengungsi, ratusan aktivis ditahan, serta pertempuran terus berlanjut di berbagai kawasan. Di sini, tugas jurnalis dan warga lokal untuk menghadirkan foto tandingan menjadi sangat penting, meski risikonya tinggi.
Suara Warga yang Tersembunyi di Balik Foto
Warga di daerah konflik sering kali tak muncul di layar berita, apalagi di foto resmi negara. Padahal, mereka yang paling merasakan dampak keputusan politik ini. Ada cerita keluarga yang harus memilih antara pergi ke TPS atau tetap bersembunyi di pengungsian. Ada pula komunitas yang boikot pemilu, tetapi suara mereka tenggelam karena tak pernah masuk bingkai kamera.
Banyak aktivis digital Myanmar mulai memakai foto sebagai senjata balik. Mereka mengunggah gambar desa kosong saat hari pemungutan suara, kursi TPS yang tak terisi, atau papan pengumuman yang sobek. Foto-foto itu memberi pesan: legitimasi bukan sekadar soal jumlah surat suara, melainkan juga soal kehadiran keyakinan publik. Tanpa kepercayaan, pemilu tinggal menjadi bayangan prosedural.
Dari kacamata etis, pemilu di tengah perang saudara menimbulkan dilema berat. Di satu sisi, ada harapan kecil bahwa proses politik bisa membuka jalan kompromi. Di sisi lain, situasi represif membuat hasil pemilu sulit dianggap sah. Menurut saya, foto-foto yang muncul nanti akan menjadi arsip moral: generasi mendatang akan menilai apakah dunia menutup mata terhadap isyarat visual ketidakadilan tersebut atau justru berani membaca makna di baliknya.
Peran Media, Sensor, dan Manipulasi Persepsi
Media lokal yang masih bertahan berada pada posisi serba sulit. Mereka dipaksa mengutip narasi resmi, sekaligus menyaksikan realitas kontras di lapangan. Banyak redaksi yang akhirnya beroperasi dari luar negeri, mengandalkan jaringan warga sebagai koresponden. Foto-foto kiriman warga kerap menjadi satu-satunya jendela alternatif bagi publik internasional untuk memahami situasi sebenarnya.
Sensor membuat arus informasi terdistorsi. Foto demonstrasi bisa disensor, sementara gambar keberhasilan penyelenggaraan pemilu justru dibanjiri promosi. Propaganda visual semacam ini bukan hal baru. Namun, di era media sosial, kecepatan peredaran foto membuat pertempuran narasi terjadi hampir real time. Rezim berusaha menenggelamkan foto kritis melalui banjir konten positif ala humas negara.
Saya berpendapat, tugas kita sebagai konsumen berita adalah menjadi pembaca foto yang skeptis. Setiap kali melihat gambar TPS ramai atau pejabat tersenyum, kita perlu bertanya: siapa yang memotret, dari sudut mana, apa yang tidak tampak? Di era konflik modern, kamera bisa menjadi perpanjangan tangan kekuasaan, tetapi juga bisa menjadi saksi bisu pelanggaran.
Pemilu sebagai Panggung, Warga sebagai Figuran
Bila melihat pola beberapa rezim otoriter, pemilu kerap berfungsi laksana panggung teater. Ada naskah, ada aktor utama, ada figuran, dan tentu saja ada fotografer resmi. Myanmar tampaknya mengikuti pola serupa. Warga dipanggil hadir bukan untuk menentukan arah negara, melainkan mengisi kursi agar foto ruangan tampak penuh. Ini bentuk pengurangan makna politik menjadi sekadar penampilan.
Kenyataan pahitnya, banyak warga mungkin terpaksa ikut demi menghindari kecurigaan aparat. Foto mereka mencoblos bisa digunakan sebagai bukti kepatuhan, meski di hati mereka tak ada dukungan. Di sini, foto kehilangan kejujuran emosionalnya dan berubah jadi simbol tekanan yang tersamar. Pose tersenyum di depan kamera bukan jaminan bahwa batin mereka merasakan hal sama.
Sebagai pengamat luar, saya merasa penting menolak normalisasi seperti ini. Kita tak boleh menganggap setiap foto pemilu sebagai tanda kemajuan demokrasi. Perlu dicek: apakah oposisi bebas berkampanye? Apakah media independen beroperasi tanpa ancaman? Apakah warga boleh tidak memilih tanpa takut dihukum? Tanpa itu semua, foto pemilu hanya menjadi poster besar yang menutupi keretakan dinding negara.
Refleksi: Membaca Foto, Mendengar Sunyi
Pada akhirnya, pemilu Myanmar menghadirkan pelajaran keras mengenai betapa mudah proses politik disulap menjadi citra semata. Foto-foto yang kelak tersisa mungkin memperlihatkan tinta di jari, antrean di TPS, atau pidato kemenangan. Namun, di balik setiap bingkai, ada sunyi yang tak terekam: suara warga yang tak percaya, keluarga korban konflik, serta generasi muda yang kehilangan harapan. Tugas kita bukan hanya melihat foto, tetapi juga berupaya mendengar keheningan di sekelilingnya. Dari sana, kita bisa menilai apakah sebuah pemilu benar-benar langkah menuju rekonsiliasi, atau sekadar kilatan kamera yang menutupi bayang-bayang kekuasaan.